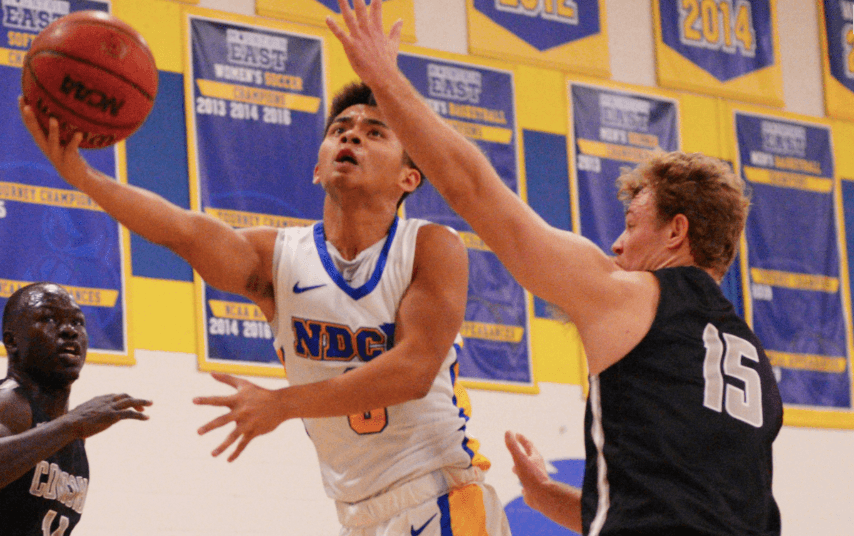Leila de Lima dan Theary Seng
keren989
- 0
‘Yang satu mencoba mengubah sistem dari dalam, yang lain memilih untuk tetap berada di luar. Keduanya berakhir di balik jeruji besi karena memperjuangkan apa yang benar.’
Ini adalah saat-saat terburuk bagi dua pengacara perempuan Asia yang saat ini mendekam di penjara karena melawan kekuasaan. Salah satunya adalah mantan senator yang dengan berani mengkritik perang narkoba yang dilakukan presiden populis. Yang lainnya adalah seorang aktivis masyarakat sipil yang menyoroti sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim otokratis. Yang satu mencoba mengubah sistem dari dalam, yang lain memilih tetap berada di luar. Keduanya berakhir di balik jeruji besi karena memperjuangkan apa yang benar.
Mereka adalah Leila de Lima dari Filipina dan Theary Seng dari Kamboja. Pada tanggal 24 Februari tahun ini, De Lima akan merayakan tahun keenam penahanannya. Seng, sebaliknya, dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada Juni tahun lalu. Kedua tuduhan terhadap mereka jelas bermotif politik.
De Lima, yang merupakan mantan sekretaris kehakiman dan ketua komisi hak asasi manusia, didakwa dengan tiga dakwaan konspirasi untuk terlibat dalam perdagangan narkoba, namun dibebaskan dari satu dakwaan pada Februari 2021, sementara dua dakwaan lainnya masih diadili. Selama persidangan, beberapa hakim yang ditugaskan menangani kasus tersebut mengundurkan diri atau memilih pensiun dini. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah saksi kunci penuntut juga menarik kembali pernyataan mereka terhadap mantan senator tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka ditekan oleh pejabat pemerintah untuk memberikan pernyataan tersebut.
Seng, seorang warga negara Amerika dan penyintas Khmer Merah, dihukum karena “konspirasi untuk melakukan pengkhianatan” dan “hasutan untuk menciptakan kekacauan besar yang mempengaruhi keselamatan publik.” Kasus-kasus tersebut terkait dengan upaya gagal Sam Rainsy, penjabat pemimpin Partai Penyelamat Nasional Kamboja yang sudah tidak ada lagi, untuk kembali ke Kamboja pada tahun 2019. Seng dijatuhi hukuman bersama dengan 60 terdakwa lainnya karena diduga mengatur kembalinya pemimpin yang mengasingkan diri tersebut, sebuah tuduhan yang dibantah keras olehnya.
Pemenjaraan De Lima dan Seng atas tuduhan pidana mencerminkan betapa memburuknya situasi politik di Filipina dan Kamboja selama setahun terakhir. Selama masa jabatan mantan Presiden Rodrigo Duterte, peringkat Filipina dalam Indeks Demokrasi Freedom House menurun dari 50.st tempat pada tahun 2016 menjadi 52n.d pada akhir tahun 2022. Penurunan di Kamboja jauh lebih nyata, dengan indeksnya turun dari 124st pada tahun 2017, ketika negara ini terakhir kali mengadakan pemilihan umum, menjadi 152n.d peringkat dari 167 negara pada tahun 2022.
Peralihan ke otoritarianisme dibarengi dengan meningkatnya korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International menunjukkan peringkat Filipina turun dari peringkat 101St tempat pada tahun 2016 menjadi 116st peringkat Kamboja meningkat dari peringkat 161 pada tahun 2017 menjadi peringkat 150 pada tahun 2022.st pada tahun 2022 tetap menjadi 2Kedua negara paling korup di Asia Tenggara, dan hanya Myanmar pasca-kenegaraan yang menduduki peringkat lebih rendah. Laporan Transparansi Internasional juga menunjukkan bahwa sistem hukum Kamboja masih menjadi salah satu sumber utama korupsi.
Dalam Indeks Rule of Law dari Proyek Keadilan Dunia, yang mengukur kepatuhan terhadap supremasi hukum melalui serangkaian indikator hasil yang komprehensif dan multidimensi, Kamboja saat ini berada di peringkat 139.st dari 140 negara, sedangkan Filipina lebih baik dengan 97 negarast tempat. Peringkat Kamboja yang berada di peringkat terbawah menunjukkan bahwa negara tersebut mendapat nilai rendah pada sebagian besar indikator, termasuk batasan kekuasaan pemerintah, penghormatan terhadap hak-hak dasar, serta peradilan pidana dan perdata. Dalam kasus Filipina, skor terendah di antara indikator-indikator lainnya juga diperoleh pada keadilan perdata dan pidana serta hak-hak dasar.
Kasus yang menimpa De Lima dan Seng memberikan gambaran (dan pembenaran) mengapa kedua negara tersebut mempunyai nilai Indeks Negara Hukum yang relatif rendah. Di kedua negara, sistem hukum telah digunakan, dan terus digunakan, terhadap pengkritik pemerintah dengan tujuan untuk melecehkan dan mengintimidasi mereka. Lawfare, yang didefinisikan sebagai “penggunaan prosedur hukum secara strategis untuk mengintimidasi dan menghalangi lawan”, menjadi hal yang biasa dalam kedua konteks tersebut. Demokrasi, seperti kata mereka, mati karena ribuan luka. Penegakan hukum tidak diragukan lagi merupakan bagian integral dari proses ini.
Di tangan pemimpin otokratis seperti Rodrigo Duterte dan Hun Sen, pengadilan dan hukum telah digunakan sebagai instrumen balas dendam politik. De Lima menimbulkan kemarahan Duterte ketika dia menyelidiki pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan Duterte saat dia masih menjabat sebagai walikota. Sebaliknya, Seng menjadi sasaran Hun Sen karena ia menggunakan koneksi internasional dan domestiknya untuk menarik perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Tuduhan yang tidak jelas terhadap mereka, dan persidangan yang diakibatkannya, jelas merupakan sebuah kepalsuan. Dalam kata-kata Seng, persidangannya tidak lain hanyalah “teater politik… (dimana) para aktor harus mengikuti naskah yang ditulis oleh para politisi.” Hal serupa juga berlaku pada De Lima.
Terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi saat ini, kedua wanita itu tetap tidak tertunduk, tidak tertunduk, dan tidak putus asa. De Lima terus menjalankan tanggung jawabnya sebagai senator terpilih dengan sangat baik hingga akhir masa jabatannya. Dia pernah berkata bahwa dia lebih suka dikirim ke penjara untuk membela kebenaran daripada masuk neraka bersama orang-orang yang menganiayanya. Akhir tahun lalu, Seng melancarkan mogok makan untuk memprotes kondisi penjaranya menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Kamboja. Dia juga baru-baru ini mulai menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Khmer saat berada di penjara. Dia sebelumnya mengatakan bahwa penahanannya hanya dapat membatasi kebebasan bergeraknya – namun tidak dapat menghilangkan kebebasan hati nuraninya.
“Kita harus ingat bahwa semua kekuasaan, tidak peduli seberapa absolutnya, akan cepat berlalu,” kata De Lima. “Yang permanen adalah kebenaran dan keadilan.”
Saat terbaik akan datang. Kebenaran dan keadilan akan menemukan De Lima dan Seng. Kami berharap, dan bersama dengan sekutu oposisi, akan melakukan upaya-upaya agar hal ini dapat terwujud secepatnya. – Rappler.com
Francis “Kiko” Pangilinan adalah ketua Dewan Liberal dan Demokrat Asia (CALD) dan ketua Partai Liberal Filipina